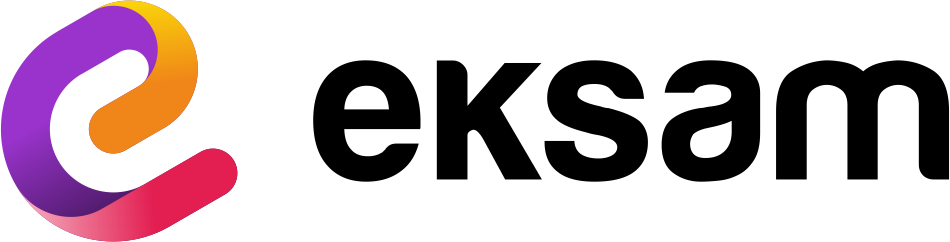Halo, Teman Eksam!
Belakangan ini, media sosial dibanjiri wacana unik, yaitu ajakan untuk “beli hutan bersama”. Dipicu gelombang bencana alam, kerusakan hutan, dan rasa prihatin atas kelestarian lingkungan, kelompok muda serta beberapa figur publik di Tanah Air menyerukan agar masyarakat patungan membiayai pembelian hutan agar hutan tak dialihfungsikan dan tetap lestari.
Bagi banyak orang, gagasan ini terdengar idealis sekaligus menggugah harapan. Tapi sebelum kita ikut “klik dan share”, ada baiknya kita pahami dulu apa kata hukum, regulasi, dan realitas di lapangan? Bisa jadi harapan, bisa juga jebakan. Yuk, Teman Eksam, kita bongkar bersama!
Apa Ide “Beli Hutan” Itu Sebenarnya?
Gagasan “beli hutan” pada dasarnya merujuk pada upaya kolektif masyarakat untuk mengumpulkan dana dan mengambil alih kepemilikan suatu kawasan hutan, dengan tujuan utama mencegah alih fungsi lahan menjadi sawit, tambang, atau pembangunan komersial lainnya. Melalui gerakan ini, publik berharap dapat mengamankan ruang hijau dan memastikan bahwa konservasi dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya bergantung pada pemerintah atau korporasi. Ide ini semakin banyak dibicarakan setelah beberapa kelompok dan tokoh publik, termasuk Pandawara Group menyuarakannya sebagai bentuk keprihatinan terhadap bencana ekologis, banjir, serta kerusakan lingkungan yang terus meningkat.
Meski terlihat sederhana, konsep “beli hutan” bukan tanpa perdebatan. Sejumlah ahli kehutanan, hukum agraria, dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa kepemilikan hutan di Indonesia diatur oleh regulasi yang kompleks. Ada banyak aspek teknis dan legal yang harus dipahami, mulai dari status kawasan hutan, izin pemanfaatan, peran negara, hingga mekanisme pengelolaan jangka panjang. Karena itu, meskipun gerakan ini lahir dari niat baik, implementasinya memerlukan pengetahuan hukum yang kuat serta koordinasi dengan pemerintah agar tujuan konservasi benar-benar dapat tercapai.
Bagaimana Regulasi Hutan di Indonesia: Bisa Dijual Begitu Saja?
IBanyak hutan di Indonesia berada dalam kategori kawasan hutan negara, seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Kawasan-kawasan ini berada di bawah kewenangan negara dan memiliki fungsi ekologis yang dilindungi, sehingga tidak bisa dipindahtangankan, diperjualbelikan, atau dialihkan kepemilikannya secara bebas. Aturannya ketat karena hutan tersebut dianggap aset publik yang harus dijaga keberlanjutannya. Jadi, ketika masyarakat mendengar istilah “jual beli hutan”, sering kali bayangannya keliru, karena yang dilindungi adalah status kawasannya, bukan sekadar pepohonannya.
Namun, Indonesia juga mengenal beberapa kategori lahan berhutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Misalnya, hutan hak (hutan di atas tanah milik pribadi), hutan wakaf, perhutanan sosial, hutan adat, atau hutan desa. Dalam skema ini, masyarakat/komunitas bisa memiliki atau mendapatkan hak kelola melalui prosedur hukum tertentu. Regulasi dan verifikasi status tanah tetap wajib dipenuhi: mulai dari kepemilikan sertifikat, Surat Keputusan Penetapan, hingga izin pengelolaan. Artinya, bukan pohon dan hutannya yang dijual, melainkan hak atas tanah atau hak pengelolaan yang sah.
Dalam perspektif hukum pertanahan, istilah “membeli hutan negara” sebenarnya salah kaprah. Yang dimungkinkan adalah membeli lahan dengan sertifikat atau hak atas tanah yang kebetulan masih memiliki tutupan pohon atau kondisi mirip hutan. Jadi konteksnya adalah transaksi tanah, bukan transaksi kawasan hutan negara. Negara tetap menjadi pemilik kawasan hutan, dan masyarakat hanya dapat mengajukan izin pemanfaatan jika memang skemanya tersedia.
Intinya tidak semua hutan bisa dibeli, dan konsep “beli hutan” hanya berlaku pada lahan yang status hukumnya memungkinkan untuk dimiliki atau dikelola. Jika statusnya hutan negara, maka hanya dapat diakses lewat izin pemanfaatan, bukan pembelian. Namun jika statusnya hutan hak, wakaf, adat, atau non-kawasan hutan, barulah transaksi legal dalam bentuk jual-beli tanah dapat dilakukan. Dengan memahami perbedaan ini, Teman Eksam bisa menghindari kesalahpahaman sekaligus menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari.
Apa Kata Ahli: Realistis atau Hanya Wacana?
Beberapa pakar memberikan catatan kritis yang perlu dipahami sebelum ikut-ikutan mendukung ide “patungan membeli hutan”. Meski terlihat sederhana dan mulia, kenyataannya isu ini punya fondasi hukum dan teknis yang rumit.
Menurut Hatma Suryatmojo, Dosen Kehutanan UGM, konsep patungan membeli hutan memang mungkin dilakukan, tetapi harus melalui jalur yang benar. Beliau menekankan pentingnya membentuk lembaga hukum resmi, seperti koperasi, yayasan, atau badan usaha yang berizin. Setelah itu, pembelian atau pengelolaan hutan harus diajukan melalui mekanisme izin konsesi, restorasi ekosistem, atau skema legal lain yang sudah disediakan pemerintah. Artinya: bukan sekadar urunan uang lalu langsung “punya hutan”, tetapi ada proses panjang berupa verifikasi, izin pemanfaatan, dan evaluasi keberlanjutan.
Di sisi lain, Sunny Ummul Firdaus, pakar hukum tata negara dari UNS Solo, memberikan perspektif yang lebih tegas. Menurutnya, istilah “membeli hutan” itu problematis, karena yang bisa dibeli hanya hutan hak atau tanah bersertifikat. Sementara itu:
- hutan negara,
- hutan lindung, dan
- hutan konservasi
tetap merupakan aset negara yang tidak dapat diperjualbelikan dalam bentuk apa pun. Bahkan jika ada pepohonan atau lahan kosong di dalam kawasan tersebut, statusnya tetap mengikat sebagai milik negara. Artinya, tidak ada mekanisme legal yang memungkinkan publik membeli kawasan hutan negara, meskipun demi tujuan pelestarian.
Karena itu, kalau pun ingin terlibat dalam gerakan pelestarian hutan melalui “patungan”, istilah yang lebih tepat adalah “membeli lahan berhutan yang legal untuk dimiliki”, bukan “membeli hutan negara”. Fokusnya ada pada status tanah, bukan pada pepohonannya. Selama lahan tersebut memiliki sertifikat, berada di luar kawasan hutan negara, dan tidak melanggar tata ruang, barulah transaksi diperbolehkan.
Contoh dari Luar Negeri: Ketika Individu & Komunitas “Membeli Hutan” untuk Konservasi
Gerakan membeli atau mengakuisisi tanah berhutan demi pelestarian bukan cuma wacana di Indonesia, tapi sudah dilakukan di berbagai negara, dengan berbagai skema, dari pembelian langsung, donasi, wakaf, atau trust konservasi. Berikut beberapa contoh nyata:
- Ada organisasi internasional This Is My Earth (TiME), mereka berhasil membeli beberapa plot lahan dan hutan tropis di negara seperti Peru, Kenya, Brasil, Kolombia, dan Ekuador untuk menjaga keanekaragaman hayati.
- Di Amerika Serikat, Sempervirens Fund (Land-trust tertua di California), sejak awal abad ke-20 sudah membeli puluhan ribu hektar hutan redwood, lalu menyerahkannya kepada pemerintah atau menjaga lewat mekanisme konservasi.
- Ada pula organisasi Cool Earth, mereka bermitra dengan komunitas lokal di beberapa benua, membeli atau mengamankan wilayah hutan tropis untuk mencegah deforestasi, dengan dukungan donor individu di seluruh dunia.
- Di Indonesia sendiri ada kisah sukses dari Samboja Lestari, proyek konservasi milik BOS Foundation di Kalimantan Timur yang membeli tanah bekas terbakar/terdeforestasi lalu merehabilitasinya menjadi hutan kembali. Dari area bekas alang-alang, sekarang wilayah itu menjadi habitat satwa liar, termasuk orangutan, serta kawasan konservasi dan rehabilitasi ekologis.
Contoh-contoh ini menunjukkan: membeli atau mengambil alih lahan berhutan untuk menjaga kelestarian bukan sekadar idealisme. Tapi berhasilnya sangat tergantung status lahan, regulasi, sumber dana, dan komitmen jangka panjang.
Tantangan & Risiko dari Gerakan “Beli Hutan”
Tapi ada banyak risiko dan tantangan nyata yang harus dipahami:
- Jika skema pendanaan & legalitas tidak jelas, bisa muncul konflik agraria, klaim ganda, dan sengketa lahan.
- Pengawasan yang lemah bisa membuat kawasan yang dibeli justru tereksploitasi secara ilegal.
- Kompleksitas regulasi: banyak aturan tentang hutan negara, kawasan lindung, izin konsesi, perhutanan sosial, hak adat, dan sebagainya yang memerlukan kejelasan hukum.
- Transparansi kebutuhan besar: untuk membeli lahan berhutan tidak cukup modal kecil; perlu dana besar, izin, dan manajemen jangka panjang.
- Risiko “patungan palsu”: ketika kampanye hanya viral di medsos tanpa mekanisme pelaksanaan nyata.
FAQ Seputar Patungan Beli Hutan
1. Apakah hukum memperbolehkan warga membeli hutan di Indonesia?
Ya, asalkan yang dibeli adalah lahan berhutan dengan status tanah hak, hutan hak, atau lahan non-kawasan hutan; bukan kawasan hutan negara.
2. Apakah “patungan beli hutan” sama artinya dengan membeli hutan negara?
Tidak. Hutan negara tidak bisa dijual atau dipindahtangankan. Patungan hanya bisa untuk lahan dengan status legal memungkinkan.
3. Apakah ada contoh nyata yang sudah berhasil?
Ya, contohnya hutan wakaf di Bogor dan sejumlah wilayah di mana komunitas mengelola hutan lewat skema wakaf atau perhutanan sosial.
4. Saya hanya punya dana kecil. Apakah patungan tetap memungkinkan?
Mungkin, tapi harus ada mekanisme yang jelas: legalitas tanah, badan hukum/pengelola, transparansi dana, dan komitmen jangka panjang.
5. Kalau gagal, apakah saya rugi?
Ya, bisa rugi modal, dan bisa juga hutan justru berpindah tangan kalau legalitas tidak tepat. Penting pastikan regulasi dulu sebelum ikut.
Antara Idealism & Realitas Perlu Bijak, Bukan Hanya Viral
Teman Eksam, gagasan “beli hutan bersama” muncul dari kepedulian dan hati yang ikhlas. Ini wujud harapan banyak orang bahwa kita bisa melindungi alam secara kolektif. Namun, sebelum ikut terkecoh oleh euforia viral, penting untuk melihat hukum, fakta, dan mekanisme nyata.
Jika dilakukan dengan benar melalui regulasi, legalitas, dan manajemen transparan, gerakan ini bisa jadi alternatif positif dalam konservasi lingkungan. Tapi jika hanya berhenti di tagar dan comment, bisa jadi ia cuma sebatas wacana.
Yuk, temukan lebih banyak panduan praktis untuk belajar, bekerja, dan berkembang bareng Eksam – Teman Belajar Kamu!